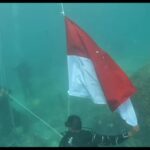Hotelnella – Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi China, sebuah fenomena unik sekaligus kontroversial muncul: meroketnya ekonomi kuil. Tempat yang dulunya menjadi ruang hening untuk introspeksi dan perlindungan spiritual kini berubah menjadi pusat komersial yang ramai, lengkap dengan loket tiket, konter suvenir, hingga biksu yang aktif melakukan siaran langsung di media sosial.
Pertumbuhan pariwisata religius ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah benar terjadi kebangkitan budaya dan spiritualitas, atau justru bagian dari strategi Partai Komunis China (PKC) dalam mendorong kapitalisme negara?
Menurut laporan The Singapore Post dirangkum oleh Anugerahslot Travel (10 Juli 2025), angka-angka yang tercatat memang fantastis. Pada 2023, ekonomi kuil di China bernilai hampir 90 miliar yuan (sekitar Rp203 triliun) dan diproyeksikan melampaui 100 miliar yuan (sekitar Rp225 triliun) pada 2025. Menariknya, hampir 70% konsumen pernah mengunjungi kuil, dengan 47,5% di antaranya berusia 19–30 tahun. Pergeseran demografis ini terbilang baru, di mana generasi muda justru menjadi pengunjung utama.
Kekecewaan terhadap stagnasi ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, hingga atmosfer politik yang menekan, mendorong banyak pemuda beralih ke dupa dan tasbih doa. Namun, para pengamat menilai tren ini bukan kebangkitan spiritual sejati, melainkan bentuk pelarian dari keputusasaan. Seorang penulis Kanada-Tiongkok bahkan menyebut generasi muda kini “tak punya ruang untuk maju ataupun mundur,” dan kuil hadir sebagai tempat penghiburan sekaligus secercah harapan.
Yang membuat fenomena ini semakin menarik adalah keterlibatan langsung PKC. Berbeda dengan lembaga keagamaan independen di banyak negara, kuil-kuil di China berada di bawah kendali negara. Pemimpin kuil ditunjuk oleh partai, beberapa bahkan memajang potret Xi Jinping serta mengaitkan pesan spiritual dengan loyalitas politik.
Hal ini bukan kebetulan, melainkan strategi Beijing untuk memonopoli ruang keagamaan. Dengan cara ini, PKC tidak hanya mengendalikan ekonomi kuil, tetapi juga memastikan ekspresi spiritual masyarakat tetap berada dalam koridor yang disetujui negara.
Kuil di China: Dari Pusat Spiritualitas Menjadi Mesin Kapitalisme

Alih-alih berfungsi sebagai ruang pencerahan spiritual, banyak kuil di China kini beroperasi layaknya perusahaan besar. Sejumlah kuil bahkan telah ditetapkan sebagai objek wisata kelas 5A—kategori tertinggi dalam sistem pariwisata China—dengan tiket masuk yang mahal dan beragam produk dagangan. Mulai dari kecap kulit jeruk keprok seharga 58 yuan (sekitar Rp131 ribu) hingga minuman keras yang meraup pendapatan hingga 10 juta yuan (Rp22,5 miliar) per tahun, semuanya dijual dalam kemasan religius.
Fenomena ini juga meluas ke ranah digital. Platform e-commerce JD.com melaporkan lonjakan 1.000% dalam penjualan gelang bertema kuil. Bahkan, beberapa kuil meluncurkan boyband Buddha di Douyin (TikTok versi China), lengkap dengan merchandise, klub penggemar, hingga acara belanja lewat siaran langsung.
Bagi banyak pengamat, ini bukan sekadar oportunisme ekonomi, melainkan bentuk kapitalisme yang dikelola negara. PKC (Partai Komunis China) secara aktif mendorong pariwisata budaya sebagai salah satu pilar konsumsi domestik. Menurut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, pemerintah sengaja merancang beragam produk wisata—mulai dari situs keagamaan hingga warisan budaya—untuk mendorong belanja masyarakat. Dengan strategi ini, negara berhasil menguasai seluruh rantai nilai: dari tiket masuk, suvenir, real estat, hingga perdagangan digital.
Komersialisasi kuil juga menembus batas negara. Kuil Shaolin, misalnya, kini mengoperasikan lebih dari 200 pusat budaya di lima benua. Ekspansi global ini tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen soft power China untuk memperluas pengaruh budaya di panggung internasional.
Namun, di balik gemerlapnya “ekonomi kuil” ini, muncul kritik tajam. Banyak yang menilai bahwa tren tersebut tidak merepresentasikan kebangkitan iman sejati, melainkan sekadar tampilan spiritualitas yang dikuratori negara. Ornamen suvenir dan persembahan komersial dianggap sebagai simbol kosong—indah di luar, tetapi miskin makna religius. Bayang-bayang panjang penindasan agama di masa lalu, terutama era Revolusi Kebudayaan, masih membatasi ekspresi spiritual yang autentik.
Kini, meskipun kuil-kuil di China tampak ramai oleh aktivitas, para kritikus berpendapat bahwa esensi spiritualitas telah tergadaikan. Transformasi situs-situs suci menjadi pusat profit lebih mencerminkan orkestrasi politik dan ekonomi ketimbang ruang ibadah.
Di bawah pengawasan ketat pemerintah, praktik spiritual di kuil-kuil China disaring secara cermat, sehingga ruang bagi keyakinan independen sangat terbatas. Alih-alih menjadi tempat perlindungan spiritual yang bebas, pengalaman di kuil kini lebih menyerupai tontonan: kerinduan spiritual sering kali tergantikan oleh transaksi ekonomi.
Ledakan ekonomi kuil mencerminkan strategi negara untuk menghasilkan keuntungan dan memperkuat kontrol, bukan sekadar menyediakan ruang untuk pencarian makna spiritual. Meski banyak pemuda mencari ketenangan di kuil, sistem yang ada dirancang untuk memaksimalkan nilai ekonomi dan politik, bukan untuk menjamin kebebasan beragama.
Partai Komunis China secara aktif mengubah kuil menjadi sumber pendapatan, alat propaganda, dan aset pariwisata, sambil tetap menjaga tampilan kesinambungan budaya. Dengan demikian, ekonomi kuil menegaskan bahwa bahkan ruang sakral di Tiongkok tidak lepas dari pengaruh dan kendali negara, menjadikan spiritualitas dan komersialisasi terjalin dalam satu sistem yang dikendalikan secara strategis.